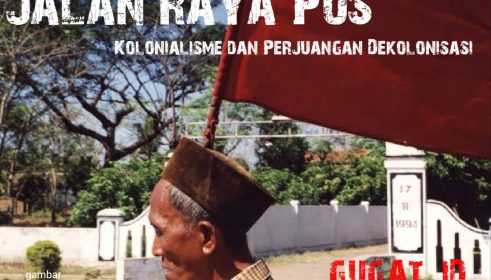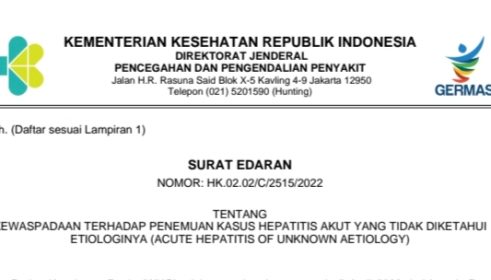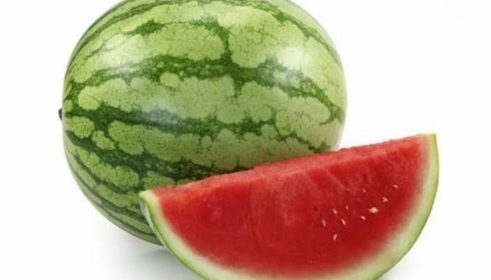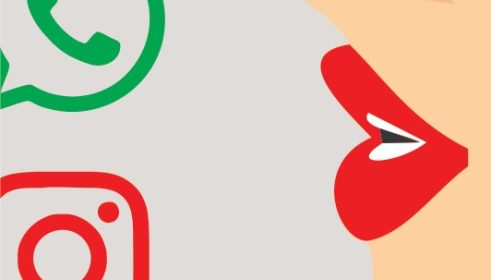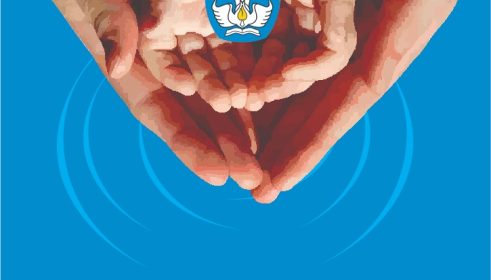Yogyakarta, gugat.id- Di tengah gegap gempita Hari Kemerdekaan, saat merah putih berkibar serempak di halaman rumah dan sekolah, tiba-tiba pandangan kita tertumbuk pada sesuatu yang mencolok: bendera hitam bertengkorak, ikon bajak laut dari anime One Piece. Sebagian orang mungkin tersenyum geli. “Ah, cuma anak-anak cari perhatian.” Tapi yang lain mungkin mengernyit: “Apa ini bentuk pemberontakan?”
Di balik kain hitam dan gambar tengkorak itu, bisa jadi tersimpan sebuah pesan: hasrat untuk bebas, namun tak ingin melukai. Generasi muda saat ini hidup di tengah gelombang budaya pop global. Mereka menyerapnya bukan sekadar untuk hiburan, tapi juga untuk membentuk identitas dan menyampaikan kritik, meski diam-diam.
Antonio Gramsci menyebut fenomena semacam ini sebagai kontra-hegemoni sebuah perlawanan halus terhadap dominasi ideologi resmi. Tanpa spanduk politik, tanpa pidato panas. Cukup dengan sehelai bendera anime. Dalam dunia One Piece, bendera bajak laut (Jolly Roger) bukan sekadar simbol kejahatan, tapi lambang kebebasan. Luffy dan kru Topi Jerami tak ingin menaklukkan dunia. Mereka hanya ingin hidup tanpa dikekang.
“Aku akan memiliki kebebasan di lautan ini!” kata Luffy. Sebuah kalimat yang bagi sebagian orang mungkin kekanak-kanakan, tapi bagi generasi muda, itu adalah deklarasi yang dalam: hidup harus dijalani dengan merdeka.
Di Indonesia, ketika simbol ini muncul bersamaan dengan bendera merah putih, ada yang menganggapnya menodai kesakralan. Tapi benarkah ini bentuk anti-nasionalisme? Atau justru cara baru untuk mencintai tanah air dengan bahasa yang mereka pahami sendiri?
Sosiolog Emile Durkheim menjelaskan bahwa ritual seperti mengibarkan bendera adalah sarana membangun solidaritas sosial. Namun, solidaritas itu tidak harus seragam dalam bentuk. Ia bisa muncul dari kebersamaan makna, meski dalam rupa berbeda. Bagi anak muda, mengangkat simbol bajak laut bukan karena ingin memberontak, tapi karena mereka merasa belum diberi ruang untuk bicara.
Michel Foucault mengingatkan, kekuasaan akan selalu melahirkan resistensi. Tapi resistensi hari ini tidak lagi dalam bentuk revolusi berdarah. Ia hadir dalam warna rambut, lagu rap, meme politik, dan ya, bendera anime. Inilah medan pertempuran baru: budaya populer sebagai arena negosiasi antara kuasa dan rakyat.
Lihatlah Zoro, tangan kanan Luffy, yang berkata: “Jika aku tidak bisa melindungi kaptenku, mimpiku tidak ada artinya.” Kalimat itu adalah tentang loyalitas, pengorbanan, dan impian. Nilai-nilai yang justru sangat Indonesia gotong royong, keberanian, setia kawan. Hanya saja, disampaikan lewat cara yang lebih nyentrik.
Maka mungkin kita perlu menata ulang cara memandang nasionalisme. Ia tak selalu harus datang dalam bentuk upacara formal atau pidato panjang. Di era global ini, cinta tanah air juga bisa hadir dalam komik, cosplay, atau sekadar bendera bajak laut yang dikibarkan dengan bangga bukan untuk melawan merah putih, tapi untuk menyuarakan: “Kami pun cinta negeri ini. Tapi biarkan kami menyampaikannya dengan cara kami sendiri.”
Karena pada akhirnya, bukankah kemerdekaan yang kita rayakan setiap Agustus adalah tentang satu hal: kebebasan menjadi diri sendiri di tanah yang kita cintai bersama?
Seperti Luffy, anak-anak muda hari ini tidak mencari kekuasaan. Mereka mencari kebebasan. Dan di lautan demokrasi ini, mungkin bendera bajak laut bukan ancaman, melainkan cermin kebebasan yang dulu kita rebut dengan darah dan air mata.